Belakangan ini, sebagaimana diberitakan media massa, perilaku curang dalam bentuk tindak pidana korupsi semakin sering terjadi. Seolah-olah fungsi agama untuk meningkatkan moral dan derajat manusia telah mengalami kegagalan. Para pejabat, yang seharusnya menjadi panutan, apakah itu PNS di kejaksaan, hakim, polisi, birokrat, anggota legeslatif, dan lain sebagainya tampak semakin kemaruk saja untuk mengumpulkan kekayaan secara tidak halal. Berikut wawancara Made Mustika dari Raditya dengan Drs. I Wayan Suja, M. Si.
Drs. Wayan Suja, M.Si, seorang dosen di Undiksha Singaraja mengatakan, “Orang Bali lebih takut melanggar tradisi daripada melanggar ajaran agama,” katanya suatu ketika saat memberikan dharmawacana di sebuah sekolah. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengapa keterpurukan bangsa semakin parah, Raditya berkesempatan datang ke rumahnya di Jl. Pulau Komodo, Gang Ayodya, Singaraja, beberapa waktu lalu. Berikut petikannya.
Secara umum, bagaimana komentar Anda melihat semaraknya umat Hindu melakukan ritual pada saat-saat hari keagamaan itu datang, termasuk kegiatan Purnama-Tilem di sekolah-sekolah?
Aktivitas yang baik, tetapi jauh lebih baik jika kesemarakan ritual juga dibarengi dengan upaya untuk mengisi diri dengan nilai-nilai kehinduan dan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika hanya ritual, agama tidak akan pernah dijadikan tuntunan dalam kehidupan pribadi dan sosial. Dalam kondisi seperti itu, bukan hanya umat yang “terbebani” akibat ritual yang cenderung semakin mengembang, tetapi agama itu secara perlahan namun pasti dituntun menuju kelenyapan. Ibarat balon yang terus ditiup, memang penampakannya semakin menarik, tetapi akhirnya … meledak. Demikian juga praktek ritual, jika tidak dituntun dengan tattwa Veda, dia hanya enak dijadikan tontonan, atau enaknya hanya pada pihak penonton. Ditinggalkannya Hindu Dharma seiring rubuhnya Majapahit dan hijrahnya krama Bali saat ini ke keyakinan lain adalah bukti kekeliruan beragama yang hanya mengurusi soal-soal ritual. Sekali lagi, ini bukan kesalahan ajaran Veda, tetapi karena kekeliruan kita dalam mengemas praktek beragama, dan malas minum susu segar Sanatana Dharma.
Sudah idealkah itu?
Sangat jauh dari ideal, apalagi kesempurnaan. Jika tiga kerangka agama hanya digarap pada satu tiang, maka bangun agama itu tidak akan kokoh. Apalagi, dalam konstruksi agama, fondasi yang sesungguhnya adalah sraddha, yang terbangun lewat pemahaman tattwa. Tanpa pemahaman tattwa dan praktek kesusilaan, bangun agama itu ibarat candi atau gedung yang dibangun di atas pasir. Sedikit saja ada gangguan, apalagi gempa, banjir, atau badai, bangunan itu pasti rubuh. Dalam kondisi itu, ornamen ritual bagaimana pun indah dan megahnya, pasti tidak akan mampu mencegah ambruknya kontruksi agama tersebut.
Mengenai banten atau sesajen. Apakah hal yang kita warisi tidak bisa disesuaikan lagi, atau dimodifikasi kalau alat kelengkapannya dirasakan memberatkan karena faktor langka atau mahal?
Sumber hukum penggunaan banten dalam praktek ritual bukan sruti (wahyu), tetapi tradisi lokal yang diciptakan oleh orang-orang bijak pada zamannya. Penggunaan banten sebagai sarana pemujaan melibatkan kerja sama manusia dan alam untuk memuliakan kebesaran Tuhan. Setiap unsur banten memiliki makna simbolik untuk mengenal hakekat diri, serta mengharmonisasi diri dengan Sang Pencipta, masyarakat, dan lingkungan. Itulah banten, bahasa spiritual untuk mengekspresikan diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan, menggunakan unsur alam sebagai sarana. Permasalahannya, karena kerakusan kita mengeksploitasi alam dan malas memeliharanya, ketersediaan sarana upakara semakin terbatas. Kini, untuk memenuhi kebutuhan ritual, Bali mesti mendatangkan janur, buah-buahan, telor, bahkan sampai semat dari luar. Sudah saatnya kita mengefisienkan penggunaan sarana upakara, memodifikasi, atau bahkan menggantikan dengan produk lokal lainnya. Jika tetap berpegang pada tradisi dengan membabi buta, maka sesungguhnya kita telah mengurbankan diri untuk masa lalu, bukan untuk kebesaran agama.
Bagaimana pendapat Anda jika seseorang menggantikan ritual dengan kirtan (melantumkan mantram-mantram) atau meditasi? Mana yang lebih utama di antara cara-cara itu?
Prakteknya di masyarakat pada komunitas tertentu, itu bukan masalah penggantian; tetapi variasi dalam mengekspresikan bakti. Dasar bakti adalah cinta, sementara cinta bisa diungkapkan dengan banyak cara. Hindu agama besar. Ibarat sebuah restoran siap saji, Hindu menyediakan berbagai menu sesuai dengan selera pelanggannya. Walaupun nama dan rupa kemasannya, bahkan juga rasanya berbeda, zat-zat gizi dalam makanan tersebut tetaplah sama. Setiap orang merdeka untuk memilih cara yang terbaik baginya untuk menghubungkan diri kepada Tuhan. Dalam Bhagawad Gita Tuhan bersabda akan menerima bakti setiap orang tanpa membedakan cara yang ditempuh oleh baktanya itu, yang terpenting adalah keyakinan, ketulusan, dan juga kesesuaian dengan petunjuk Veda (vidhi drstah). Dalam kaitan dengan pembinaan umat, Smerti menyebutkan upakara yajna cocoknya pada zaman Dwapara, sedangkan pada Kali Yuga sekarang ini, ada dua cara dianjurkan, yaitu namasmaranam dan danam (dana punya). Mana yang paling mulia, tentu yang paling mampu mengantarkan diri kita mencapai jagathita dan kelepasan, atau setidaknya ketenangan jiwa.
Banyak orang mengatakan kejujuran kini semakin langka. Berikan alasan mengapa kondisi itu bisa terjadi?
Penyebabnya karena terjadi pergeseran jiwa zaman. Jiwa zaman sekarang adalah uang, karenanya semua diukur dengan uang. Keuangan itulah yang mahakuasa. Apa yang sekarang ini tidak bisa dibeli dengan uang? Kelulusan dan nilai studi, gelar akademis, jabatan, bahkan sampai harga diri seseorang, semuanya tunduk pada uang. Dalam kondisi seperti itu, kejujuran seolah terpinggirkan. Bahkan, untuk berkata jujur saja kita perlu mohon ijin. Maaf, jika boleh saya berkata jujur… Kejujuran selalu dipandang sebagai ancaman bagi mereka yang curang dan pembohong, dan sayangnya kecurangan dan kebohongan itu justru melekat pada penguasa. Dalam cengkeraman atmosfer ketidakjujuran seperti itu, jujur berarti hancur; sebaliknya tidak jujur akan selalu mujur. Kondisi itu menyebabkan, suara hati tidak akan pernah terdengar karena sangat lemah, dan pasti kalah oleh suara perut!
Secara umum masyarakat yang berpendidikan kini jumlahnya meningkat. Mengapa masalah kejujuran tidak sebanding dengan peningkatan jumlah warga yang mengenyam pendidikan?
Lembaga pendidikan kita memang lupa melatihkan kejujuran. Sekolah dan perguruan tinggi cenderung hanya menyiapkan siswanya agar mampu mencari kerja, bukan menyiapkan diri agar bisa hidup dengan benar. Karena hanya dilatih mengasah otak, maka hati menjadi tumpul dan karatan. Itulah sebabnya, banyak orang cerdas kepalanya, tetapi sangat tidak cerdas hatinya. Produk pendidikan seperti itu sangat berbahaya. Orang yang tidak mengenyam pendidikan, yang disebut orang bodoh hanya menyusahkan dirinya atau maksimal keluarganya; tetapi orang pintar yang tidak jujur bisa membahayakan seluruh bangsa, bahkan seluruh kehidupan di muka bumi ini. Rahwana, Sakuni, Hitler, dan para koruptor yang bermunculan saat ini adalah contoh orang-orang pintar produk pendidikan yang gagal.
Jika kejujuran semakin langka, bagaimana cara memperbaikinya? Apakah jam pelajaran agama perlu ditambah?
Tidak perlu. Untuk membangkitkan kembali kejujuran dari mati surinya, hanya perlu penyadaran dan panutan, bahwa kejujuran merupakan hal yang paling utama dalam beragama, dan nilai tertinggi dalam harga diri seseorang. Tanpa kejujuran, sesungguhnya kualitas manusia jauh lebih rendah dari pada binatang. Sampai saat ini belum ada binatang berbohong, kecuali jika dilatih oleh manusia. Menambahkan jam pelajaran agama untuk melatih kejujuran, itu mubazir! Bahkan, memberikan peluang untuk munculnya ketidakjujuran yang baru. Kejujuran sesungguhnya tidak terlalu perlu diajarkan, tetapi sangat mendesak untuk dicontohkan dan dibiasakan. Dalam hal ini, orang tua, guru, masyarakat dan pemerintah adalah panutan bagi setiap anak dalam memupuk kejujuran. Jika anak berbohong, orang tua dan gurunya perlu introspeksi diri. Jika kejujuran langka di masyarakat, maka penguasalah yang menjadi sumber kebohongan itu.
Jika diminta memberi saran kepada pemerintah, mana yang lebih baik untuk dipilih antara pendidikan budi pekerti dengan pelajaran agama?
Bagi saya, bukan mata pelajarannya yang penting. Malah, jika ada ruang untuk memberikan saran, saya sarankan untuk melakukan reposisi dan restrukturisasi kurikulum. Pendidikan moral perlu dicontohkan dan dibiasakan sejak dini, mulai TK. Di SD hanya belajar calistung (baca, tulis, hitung) dan memantapkan karakter. Setelah di SMP barulah diperkenalkan berbagai cabang ilmu dengan semakin memantapkan nilai-nilai karakter dalam keterpaduannya dengan nilai-nilai ilmiah. Dengan demikian, nilai moral, karakter, atau budi pekerti tidak perlu diajarkan sebagai mata pelajaran tersendiri, tetapi terintegrasi dengan seluruh mata pelajaran yang ada. Dengan demikian, membangun karakter bukan hanya tugas guru bidang studi tertentu, tetapi swadharma yang melekat pada jabatan pendidik.
Banyak pengamat juga mengatakan, di balik sisi-sisi positif UN, konon ada pula sisi-sisi yang tidak baiknya. Katanya, UN menyuburkan kecurangan dan mengerdilkan kejujuran. Bagaimana pendapat Anda?
Selama keberadaan fasilitas pendidikan dan SDM belum memadai seperti saat ini, saya termasuk orang yang tidak setuju dengan adanya UN, apalagi untuk menentukan kelulusan dan penerimaan di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jika dipaksakan, maka kepentingan politiklah yang menjadi panglima. Dalam dunia politik, ketidakjujuran bukan sesuatu yang luar biasa. Demi nama baik, kepala daerah menginstruksikan agar kepala sekolah “menyukseskan” UN, selanjutnya kepala sekolah “membekali” guru, dan tim guru menyusun “strategi.” Hasilnya, UN sukses dengan mengorbankan kejujuran, dan semua berbangga atas prestasi bohongan yang telah diraih. Bagi saya, ini benar-benar bencana. Jika lembaga pendidikan telah diatur dengan kekuatan dan kekuasaan politik, maka sesungguhnya kita telah menyiapkan diri untuk menyambut kehancuran bangsa.
Di bidang sosial kebangsaan, akhir-akhir ini kasus korupsi nampak semakin menggurita. Dikaitkan dengan moral-keagamaan, mengapa soalah-olah agama gagal membendung nafsu manusia untuk korupsi?
Bukan seolah-olah, tetapi memang gagal! Semua ini terjadi karena pelajaran agama telah salah sasaran. Pengajaran agama semestinya lebih menekankan pada pelembutan hati, sehingga membuat orang menjadi cerdas hatinya. Prakteknya sekarang, pelajaran agama baru menyentuh kecerdasan otak, sehingga muncullah orang-orang munafik yang suka memperalat ayat-ayat suci untuk membenarkan perilakunya, termasuk untuk korupsi. Di sisi lain, masyarakat juga berkontribusi terhadap suburnya perilaku amoral itu. Sekarang ini, harga diri seseorang tidak diukur dari perilakunya, tetapi berdasarkan apa yang dikonsumsinya, apa fasilitas dirinya, dan apa jabatannya. Singkatnya, proses tak penting, yang penting produknya. Akibat lebih lanjut, tuntunan agama agar kita mencari ketenangan, telah bergeser menuju kesenangan. Karena kesenangan itu tanpa batas, maka orang-orang seperti itu tidak bisa lagi makan memakai sendok dan garfu, tetapi memakai “sekop” dan “cangkul”.
Saran apakah yang dapat disampaikan agar manusia Indonesia, terutama generasi mudanya, menyadari bahwa kejujuran lebih utama dari kekayaan?
Mesti diberikan contoh dan bukti, bahwa kenikmatan jabatan dan kekayaan hanya bersifat sementara. Orang bisa saja meraih jabatan, dan apa saja dengan cara tipu-tipu, tetapi Hukum Karma tidak bisa disuap. Semua perbuatan akan mendatangkan pahala yang setimpal. Siapa saja yang mempermainkan hukum, maka dia akan dipermainkan oleh hukum itu sendiri. Dharma eva hato hanti. Sebaliknya, siapa yang menjaga kejujuran, dialah yang akan diselamatkan oleh kejujuran itu sendiri. Dharmo raksati raksitah. Karena itu, agama selalu menekankan agar kita berbuat jujur, karena kejujuran adalah mahkota kehidupan. Kejujuran adalah kebenaran yang paling utama, satyam paramadharma, dan pasti menang, satyam eva jayate. Dengan kejujuran orang bisa meraih kekayaan, tetapi untuk berbuat jujur orang tidak perlu kaya terlebih dulu.
Kembali ke soal ritual, maraknya ritual apakah mencerminkan keberhasilan pendidikan agama di masyarakat?
Sama sekali tidak, bahkan lebih sering menampilkan wajah kemunafikan. Disebut munafik manakala kesemarakan ritual tidak seiring dengan kehalusan budi, dan keluhuran perilaku. Contohnya, ritual caru dengan berbagai bentuknya semakin marak, tetapi alam Bali justru semakin tercemar oleh sampah, termasuk sampah plastik. Upacara manusa yajna, terutama “potong gigi” dan pernikahan semakin megah; tetapi perselingkuhan, perjudian, dan korupsi justru semakin terang benderang. Upacara ngenteg linggih semakin marak, pencurian pratima dengan melibatkan warga lokal pun juga tidak kalah gencarnya. Atas dasar itu, jika ritual tidak menyebabkan perilaku umat menjadi lebih baik, tidak ada transformasi diri, itu adalah ciri kegagalan pendidikan agama, yang hanya akan melahirkan anak-anak haram, seperti munafikisme, premanisme, bahkan terorisme.
Ada orang mengatakan, keberhasilan pendidikan agama akan lebih tepat bila penilaian didasarkan atas perbuatannya, bukan pada kesemarakannya melaksanakan ritual, bagaimana komentar Anda?
Saya sangat setuju. Religion is action! Agama mesti muncul sebagai pemberi solusi atas masalah yang dihadapi pribadi dan masyarakat, bukan sekedar menghibur dengan aktivitas ritual yang bersifat simbolik. Lewat doa-doa dalam ritual kita bisa memohon tuntunan agar mampu menghadapi dan memecahkan masalah, tetapi bukan doa itu yang akan menyelesaikan masalahnya. Masalah mesti dipecahkan dengan tindakan nyata, dan di situlah peran agama sebagai penuntun. Dalam pandangan saya, pengetahuan agama mesti diwujudkan dalam perilaku. Ritual itu baru simbol, bukan esensi agama yang sesungguhnya. Fungsi ritual hanya mengingatkan dan menyadarkan, bukan memecahkan masalah yang sesungguhnya. Atas dasar itu, ritual itu penting, tetapi bukan yang terpenting. Ibarat pohon, kualitasnya tidak ditentukan oleh lebat bunganya, tetapi dari kualitas buahnya.
Terima kasih.
sumber : http://majalahhinduraditya.blogspot.co.id/2013/06/kejujuran-terpinggirkan-semuanya-tunduk.html
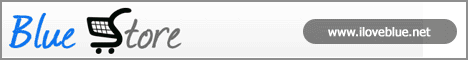
Tidak ada komentar:
Posting Komentar